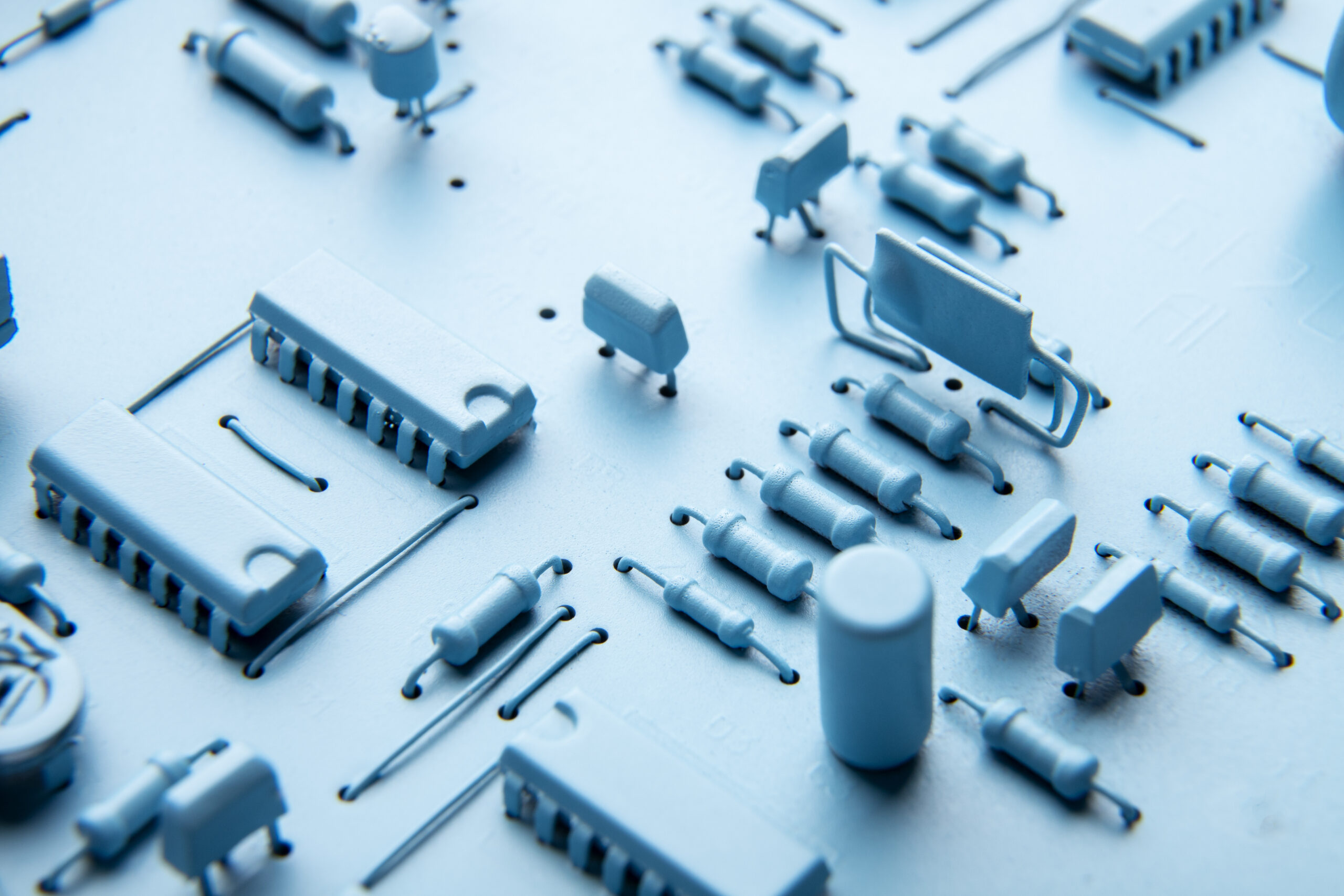Kampanye dengan musik populer atau dangdut semakin tidak disukai gen z. Salah satunya mungkin alasan dari teori Adorno. Adorno pernah berkata bahwa kepentingan penguasa kadang membuat budaya kita menjadi budaya popular dan murah. Mungkin penjelasannya begini, budaya itu memiliki keunikannya. Kita harus belajar untuk mencerna dan menikmati segala sisi dari kebudayaan yang ada. Ketika setiap penikmat bisa menikmati budaya dengan cepat dan instan, maka banyak sisi keunikan budaya itu hilang.
Dalam dunia kampanye, semua tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghadirkan dan menikmati budaya yang berkualitas. Anggap saja seperti ini. Setiap harinya, di masa kampanye, ada banyak panggung yang harus diisi oleh kandidat. Sehingga, panitia dari setiap capres harus memberikan hiburan yang mudah, murah, dan bisa dinikmati oleh siapapun. Karena inilah secara teori, produksi seni populer sangat dibutuhkan. Tidak hanya di indonesia, di Amerika sebagai negara maju pun mereka melakukan hal yang sama. Dahulu, mungkin kita bisa melihat bagaimana John Adams, Einsenhower, JFK, dll. Memiliki lagu khusus untuk berkampanye. Semua lagu itu disesuaikan dengan trend. Tetapi, selain obama, kandidat presiden Amerika pasca tahun 2000 tidak memiliki lagu khusus untuk berkampanye. Hal ini dikarenakan mencomot lagu populer untuk kampanye itu lebih mudah dibandingkan mempopulerkan lagu sendiri. Walau sedikit berbeda, tetapi prinsipnya sama. Membawa seni populer di masa kampanye itu sangat memudahkan pesan politik mudah terkirim.
Panggung dangdut dan musik viral di sosial media pasti masih akan menjadi warna di setiap kampanye 2024. Itulah mengapa ada teori bahwa penguasalah yang membuat seni menjadi populer untuk kepentingannya. Dengan banyaknya musik senja, musik elektonik, dll. Yang menjadi favorit di kalangan gen z, tentu saja lagu-lagu itu sangat segmented dan bukan lagu popular. PR berikutnya adalah bagaimana gen z menemukan cara baru untuk bisa ikut dalam dunia politik tanpa embel-embel seni populer.
Konstituen Antidangdut
- March 30, 2024
Tulisan Terbaru
- All Post
- Aktivisme
- Blog
- Budaya
- Ekonomi
- Kelas Inspirasi
- SDA
- Sorotan
- Teknologi